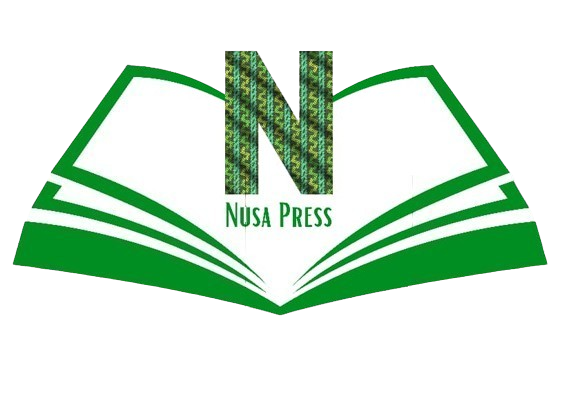Kutatap hamparan sawah yang menguning keperakan dicumbu sinar matahari sore. Indah. Sesekali kulihat pucuk-pucuk tanaman padi melambai-lambai diterpa angin sepoi. Memukau. Nun jauh di sana, para petani berjalan mengekor di pematang sawah hendak pulang. Aku duduk santai menyanggah tubuh kekasihku yang bersandar di pangkuanku. Ah, sepertinya tak ada hari yang lebih indah dari sore ini.
“Kak, aku takut.” Vina berbisik lamat-lamat, mendekatkan mulut mungilnya ketelingaku. Dapat kurasakan harum nafasnya.
Kutatap bundar wajahnya yang cantik.
“Aku takut tempat indah ini menjadi kenangan terburuk dalam hidupku, Kak Vino.”
Cepat-cepat aku menggeleng, memeluknya erat-erat. Kuletakkan daguku di atas hitam rambutnya.
“Aku tidak akan pergi jauh-jauh darimu, Sayang. Aku akan selalu ada di setiap langkah hidupmu. Percayalah, kamu tidak akan pernah lepas dari pelukanku. Kamulah pendamping hidupku. Iya, hanya kamu. Itulah janjiku.”
Vina tersenyum, manis sekali. Aku menangkap rasa lega dianggun wajahnya.
“Tapi aku takut taqdir tidak berpihak kepada kita, Kak.” Vina berkata serak, sempat terlihat gelisah.
Kini aku memeluknya sambil menggenggam erat-erat tangannya, menatap meyakinkan, berkata memastikan, “Kamu adalah yang pertama sekaligus yang terakhir, Sayang. Aku akan selalu menjagamu di setiap hirup-hembus nafasku. Aku akan melindungimu di seiring hari-hari yang datang dan pergi. Membuat kamu tersenyum adalah kewajibanku. Membuatmu tertawa adalah tugasku. Jangan hawatir, Sayang. Aku ada di dekatmu. Dan tempat ini, iya, hamparan sawah yang menguning di bumi yang indah dan subur ini adalah saksi bisu kata-kataku.”
Vina tersenyum untuk kesekian kalinya. Bangga hatiku, senang jiwaku melihat pujaan hatiku tersenyum simpul.
“Mulai sekarang sampai selamanya aku akan memegang janjimu, Kak Vino.” Sejenak ia menatap mataku lalu memendamkan kepalanya kepangkuanku. Aku tersenyum bahagia. Tuhan, jika dia adalah hadiahMu untukku, kasih tahu aku bagaimana caranya agar aku bisa membuatnya bahagia. Namun jika dia bukan untukku, kasih tahu aku bagaimana cara melupakannya. Disela-sela senyumku itu aku berbisik kepada Tuhanku.
Aku dan Vina melangkah pulang dengan senyum merekah.
“Eh, Arif, sejak kapan kamu ada di sini?” Tanyaku basa-basi melihat Arif duduk santai menikmati pemandangan hamparan sawah yang menguning. Eh, dari saking bahagianya sampai-sampai aku lupa bahwa Arif bisu. Walaupun bisu aku berani bertaruh, cewek mana yang tidak jatuh hati menatap wajahnya.
Arif hanya tersenyum.
Saat kami lewat di depannya, kulihat ia tersenyum indah kepada Vina. Indah sekali senyum anak bisu ini. Aku berbisik dalam hati.
Diam-diam aku memperhatikan tentang dua senyum itu. Kutaksir, itu adalah senyum terindah yang pernah kulihat dari Vina dan Arif. Bergetar hatiku. Curiga dan cemburu itu datang dengan sendirinya. Tapi cepat-cepat aku menepisnya. Aku percaya Vina. Aku tahu siapa dia.
Beberapa detik kemudian kami telah membelakangi Arif. Kulirik Vina, dia menoleh ke belakang. Aku ikut menoleh. Kusaksikan dua mata itu bertemu seperti sedang berbicara lewat sebuah isarat. Jiwaku kembali bergetar. Dan, hadir sudah rasa curiga itu di dalam hati meski hanya sekilas saja. Cepat-cepat aku menepis rasa kotor itu dan berbisik minta maaf di dalam hati. Ah, aku percaya kepada Vina. Forever.
***
Ditempat yang sama aku duduk menatap padi yang menguning. Keindahannya tidak kalah dengan sore hari. Lebih indah malah. Kulihat pucuk-pucuk padi tidak melambai seperti siang atau sore hari, mungkin saja karena terasa berat menggendong embun pagi. Kabut tipis membentuk lingkaran di atas kepala. Cericit burung bertalu-talu seperti alunan musik yang mengiringi keindahan pagi. Inilah separuh alasan mengapa aku tidak pernah lelah menunggu Vina. Dan alasan separuhnya lagi adalah orang yang aku tunggu terlalu berharga buat aku. Demi dia, menunggu berjam-jam pun tak akan pernah bosan.
Kulihat dari arah kanan, lalu lalang para petani dengan wajah ceria menatap tanaman padinya. Kudengar sayup-sayup obrolan mereka tentang padi. Aku bisa menangkap dari perbincangan senang mereka. Tentu saja tidak pernah lepas dari padi dan hama. Bagi mereka tentu tak ada hal yang lebih indah dari pada hari panen tanaman padinya.
“KakVino.”
Aku mendengar kalimat itu. Suaranya lembut. Aku kenal pasti siapa pemiliki suara itu. Dengan semangat aku menoleh. Dia tersenyum. Aku balas tersenyum. Senyum itu yang kurindukan. Senyum itu yang sering kali mengusik tidurku.
“Maaf aku lambat, Kak Vino.” Vina berkata pelan, merasa bersalah.
Sikap itu yang membuatku tidak bisa melepasnya. Merasa bersalah, selalu introspeksi diri.
“Sini, Sayang.” Aku mengerlingkan mata, tersenyum nakal.
Ia mendekat patah-patah, duduk disebelahku, lalu menyandarkan tubuhnya dengan mesra. Oh, Tuhan, adakah yang lebih indah dari yang kujalani sampai kini? Aku bertanya dalam hati. Seperti biasa kami saling melempar senyum dan saling menukar kata indah bernunsa rayuan. Menjual janji-janji manis, membangun mimpi indah di kursi pelaminan yang menggetarkan hati, bahkan mengukir sketsa-sketsa masa depan bersama. Imajinasi yang terlampau indah, bukan?
“Sayang, di dunia ini ada dua hal yang membuatku betah.” Aku berbisik renyah di dekat telinga Vina.
Vina bertanya, tersenyum manja.
“Pertama adalah kamu. Dan kedua adalah tempat ini.”
Vina tersenyum riang. Aku menangkap guratan rasa bahagia di ayu wajahnya.
“Tapi aku bingung, Sayang.”
“Bingung kenapa, Kak Vino?” Vina bertanya penasaran, menatap lamat-lamat.
“Iya, karena aku dihadapkan terhadap dua keindahan yang teramat indah. Aku dibingungkan untuk memilih mana yang lebih indah antara indah wajahmu dengan indahnya tempat ini, alam ini, bumi ini, dan lingkungan tempat aku menyulam rasa ini, Sayang.”
Vina mencubit lenganku, bermanja-manja. Tertawa senang.
“Terus Kakak milih yang mana?”
Aku tahu dia sedang memancingku untuk melanjutkan kata-kata lebayku.
“Tentu aku akan memilih tempat ini, Sayang.”
Vina tersenyum, tapi senyumnya masam. Tampak sekali bahwa ia kecewa. Aku tersenyum.
“Tentu itu adalah pilihan yang paling tepat, Sayang.”
Aku memancingnya berkomentar untuk memastikan apakah ia kecewa atau malah marah. Ternyata benar, ia tidak menaggapi kata-kataku. Aku mengulanginya. Dia tetap diam bergeming, berpura-pura menatap hamparan padi yang seperti tersenyum melihat wajah murung gadis idamanku.
“Eits, tunggu dulu. Jangan marah dulu, Sayang. Aku memilih tempat ini indah karena ada kamu. Kalau tidak ya….” Aku tidak melanjutkan kata-kataku sebab aku melihat raut bahagia yang bersembunyi di wajahnya. Aku lebih memilih melanjutkan dengan perbuatan. Iya, aku melanjutkan dengan ciuman mesra di lembut pipinya. Ia tersipu malu. Kikuk tidak dapat lagi bercakap-cakap.
“Benar, Sayang. Indahnya tempat ini karena terkena bias indahnya…”
“Iya, iya, iya si raja gombal.” Vina memotong kalimatku, kemudian mencium balas pipiku.
“Tapi aku lebih memilih yang masuk akal kenapa tepat ini indah dan terawat, Kak Vino. Kenapa tempat ini memukau tidak seperti tempat-tempat lain yang telah dikuras habis oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jawabannya adalah karena pengaruh kata-kata guru kelasku. Dia berkata dengan lantang bahwa, ‘kita harus memelihara lingkungan hidup kita, kita harus melestarikan bumi tempat kita berpijak, dan ada hal yang perlu diperhatikan, sejauh mana kita memberikan yang terbaik terhadap lingkungan hidup kita bukan malah sebaliknya menguras habis-habisan sumber daya alam diluar ambang batas kewajaran’.”
“Pak siapa itu, Sayang?” Aku bertanya penasaran.
“Siapa lagi kalau bukan Pak Kumis,” jawab Vina pendek sambil senyam-senyum.
Sontak aku tertawa, mengacak-ngacak rambutnya.
“Ya Tuhan, anak sekarang mau bergurau sama calon mertuanya. Aku aduin nanti sama papaku biar…”
Aku tidak sempat melanjutkan kata-kataku. Vina lebih dulu menutup mulutku. Aku berusaha melepas, Vina berusaha menahan. Tanpa terasa kami bergulingan di atas rumput yang kami duduki. Oh Tuhan, tak mungkin ada keindahan yang bisa menandingi pagi ini.
Satu jam berlalu tanpa terasa. Kami melangkah pulang dengan senyum penuh kemenangan. Namun lagi-lagi aku selalu bertemu dengan Arif. Seperti biasa kami menyapa Arif yang sedang duduk santai menikmati pemandangan di depannya. Menikmati hamparan luas bumi tempat kami berpijak. Bumi kami yang indah dan terawat.
Jelas-jelas aku ingin tahu, dengan siapa pemuda tampan bisu itu datang kesini. Dan untuk apa. Tapi aku bingung bagaimana caranya. Dan hatiku kembali digetarkan dengan dua mata yang saling beradu tajam. Jiwaku kembali didesirkan dengan senyum simpul yang saling membalas. Aku sempat bingung, curiga, atau cemburu bahkan. Sudahlah, aku lebih memilih menepis pikiran itu. Aku percaya Vina, sosok jelita yang periang dan suka senyum kepada siapa pun.
***
Pagi dan sore ditiap hari minggu aku rutin bertemu dengan Vina di tempat yang sama. Tempat itu memang indah, mulai dulu sampai sekarang. Lima tahun lebih aku menjalin hubungan bersama Vina, aku tidak pernah merasa bosan dengan tempat itu. Juga tidak pernah terlintas rasa bosan untuk bertemu dengan Vina. Tapi ada satu hal yang unik di minggu pagi dan sore kami betemu dengan Vina, kami selalu berpapasan dengan Arif. Ah, sudahlah, dunia ini memang unik dan lucu.
Satu bulan telah kujalani tanpa tarasa. Saat ini aku harus berangkat keluar kota untuk berlibur. Liburan pemberian papa karena nilai UNku tertinggi sekotaku. Aku bahagia bukan main karena telah membuat kedua orang tuaku bahagia. Tapi ada satu hal yang mengurangi kebahagiaanku. Aku tidak diperbolehkan berlibur bersama Vina. Alasan orang tua ada benarnya juga, takut-takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Malam hari sebelum berangkat aku dihantui rasa bimbang yang teramat sangat. Berat hatiku. Gelisah jiwaku. Aku bingung. Malam itu juga aku menghabiskan waktu bersama Vina di hamparan sawah tempat kami bertemu. Kulihat rembulan mengintip malu-malu di balik tumpukan mendung.
Usai menikmati malam perpisahan, aku langsung mengantarnya pulang. Malam itu senang sekaligus sedih bersatu padu dalam hatiku. Maklum saja karena inilah awal kali aku berpacaran. Kuperhatikan dengan sembunyi-sembunyi tingkah Vina. Ia tersenyum membaca pesan di telefon genggamnya.
“Dari siapa, Sayang? Sepertinya teramat bahagia?”
Vina cepat-cepat menggeleng, “Hanya teman, Sayang.”
Aku mengangguk. Aku percaya Vina. Dia adalah cinta sejatiku.
Tetapi esok-esok, cepat atau lambat, aku baru tahu, siapa dia sebenarnya.
***
Sebelum berangkat, aku meluangkan waktu untuk mengunjungi hamparan sawah dengan pucuk-pucuk padi menguning itu. Itulah tempat romantis kami dalam mengadu rasa. Itulah bumi dimana kami berpijak melepas rindu bersama Vina. Sebuah tempat yang terawat rapi, indah menyulap mata, dan bebas polusi. Aku cinta bumiku. Aku cinta sekolahku karena tiap minggu mengadakan kerja bakti untuk merawat lingkungan. Oh Tuhan, terima kasih ya karena telah menaruh aku dilingkungan orang-orang yang mencintai bumi dan alam sekitar.
Aku tersenyum menatap bumiku. Aku mencintai lingkungan tanah kelahiranku sama seperti aku mencintai Vina. Dan ternyata, nanti-nanti, sadar atau tidak, inilah senyum terakhirku melihat keindahan hamparan sawah dengan pucuk-pucuk menguning itu. Aku berbalik arah, menatap sekali lagi hamparan sawah menguning itu dengan senyum bahagia. Saat itulah, saat aku hendak berpaling, kertas putih terlihat tanpa kusengaja. Hatiku merasa tergerak untuk mengambilnya.
Kuambil kertas itu dengan tangan gemetar.
Surat? Aku berbisik dalam hati.
Dan, remuk sudah hati ini saat sepasang mataku menyapa rangkaian huruf demi huruf yang duduk rapi di atas kertas itu.
Vina, ini tidak mungkin? Mulutku gemetar, hatiku berserakan.
***
Buyar sudah keindahan kota berliburku. Kota yang kuidam-idamkan mulai dulu sampai sekarang. Aku tidak menemukan gelora hasrat lagi untuk pergi ke sana. Tapi apalah daya, hari ini, mau tidak mau, aku harus pergi. Kulangkahkan kaki meninggalkan kota kelahiranku, bumiku yang sejuk dan terawat. Aku pergi dengan hati yang hancur. Aku pergi dengan masalah yang belum selesai. Aku pergi dengan kebimbangan.
Satu minggu berjalan tanpa terasa. Tak ada yang menyenangkan dari liburanku. Justru yang ada hanya rindu yang menyesaki dada. Aku ingin pulang, titik. Aku tidak betah tinggal di sini, sendiri tanpa melihat senyum Vina. Aku ingin tahu kabar Vina. Sudah satu minggu disiksa dan diburu oleh rasa curiga dan rasa penasaran. Curiga dengan tulisan surat Vina. Penasaran dengan kabar Vina.
Besok pagi aku harus pulang. Dan sekarang, malam ini aku harus menikmati malam dengan menatap keindahan taman kota terindah yang pernah kulihat ini. Namun kalau boleh jujur, keindahan kota kelahiranku jauh lebih indah dari kota liburku. Sungguh.
Kunikmati malam ini dengan senyum lega. Sepasang mataku bergiliran menatap pemandangan yang memukau di sana-sini. Oh, aku memuji Tuhanku di dalam hati. Malam ini akan menjadi lebih bermakna jika aku berjalan bersama Vina. Dan saat itulah, saat aku menatap bergantian pernak-pernik keindahan taman kota liburanku, saat itulah sosok yang tidak asing lagi sedang duduk manis bersama seorang laki-laki. Jelas sekali laki-laki itu tidak asing lagi buat aku.
Perlahan kudekati dengan langkah berenergi penasaran. Oh Tuhan, benarkah ini nyata? Berulang kali aku mengucek mata. Tidak mungkin, ini tidak mungkin.
“Vino, tunggu, kamu salah paham. Izinkan aku menjelaskan. Please.” Vina berdiri, melangkah mendekatiku.
Aku menggeleng kecewa.
“Kuharap kamu jangan marah dulu, please. Biar kujelaskan semuanya. Oke. Arif itu adalah….”
“Cukup.” Aku membentaknya keras. Vina terkejut, wajahnya pucat. Bocor sudah kantong air matanya.
Arif terlihat berdiri hendak melangkah. “Berhenti, jangan ikut campur urusanku. Aku tidak mau siapapun mengeluarkan suara dan pendapat diantara aku dan wanita munafik ini. Ini urusan pribadi bukan urusan publik,” bentakanku tak kalak keras juga untuk Arif, membuat Arif berhenti dan menggeleng kepala. Aku emosi, sampai-sampai aku lupa bahwa Arif tidak bisa berbicara.
“Dan, untuk kamu si munafik murahan, saat ini, malam ini adalah malam terakhir bagiku untuk bertemu denganmu. Hampuslah namaku di dalam hatimu karena namamu dengan sendirinya telah terhapus di malam ini juga. Jangan pernah ingat aku!” Aku menuding wajahnya dengan amarah yang meluap-luap lalu pergi meninggalkannya.
Vina berlari mengejarku, memanggilku dengan suara terbata. Dia memelukku dari belakang. “Jangan tinggalkan Vina, Kak, Vina tidak ingin kehilanganmu. Kakak salah paham.” Vina menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasahi baju belakangku.
Sontak aku berbalik arah, melepasnya kuat-kuat. “Jangan sentuh aku lagi wanita berkepala dua. Wanita berkedok cantik tapi hatinya busuk. Dan kini aku tahu siapa kamu yang sebenarnya. M-u-n-a-f-i-k.”
Aku melangkah menjauh, meninggalkan Vina tanpa berpaling. Sesampai di depan mobil sekilas aku berpaling untuk memastikan sandiwara kepura-puraanya. Tapi yang kulihat, ia menangis memanggil-manggil namaku, jatuh bangun dengan darah di lututnya. Seketika nuraniku mengecam perbuatanku. Aku bingung. Jika itu pura-pura lalu kenapa dia sampai Malam ini berakhir sudah cerita-cerita indah itu. Cerita yang melahirkan lembar-lembar kenangan dan jejak masa lalu yang akan terlipat indah dalam ingatan. Nanti atau esok akan tertulis cerita baru di halaman yang baru. Juga akan lahir episode kehidupan cinta berikutnya. Namun teruntuk kamu Vina, cantik wajahmu, manis senyummu, dan anggun tawamu tidak akan pernah lepas dari ingatanku. Sampai kapan pun. Meski aku telah memilih hati lain.
Dan, sesampai di kota kelahiranku, di sana rasa sesal itu baru datang merajah-rajah hatiku. Sayang sekali rasa sesal itu datang terlambat. Jika tidak, maka tidak akan ada tangis duka antara aku dengan Vina.
***
Sesampai di halaman kotaku, aku dikagetkan dengan kerusakan-kerusakan. Sejauh edaran pandangku, tidak ada lagi rumah mentereng, tidak ada lagi rumah bersusun dengan corak eropa, tidak ada lagi hamparan sawah yang menguning, tidak ada lagi pemandangan-pemandangan asri nan elok. Lihatlah, bumiku, lingkunganku, tanah tumpah daraku, dan tempat dimana kau menghabiskan masa kecilku sudah tidak seindah dulu lagi. Semuanya rusak total. Tanpa izinku, air mata ini mengalir perlahan.
Aku berlari mencari rumahku. Tidak ada gugusan-gugusan rumah kecil yang menderet di kampungku. Semuanya rata. Aku berlari ke arah kanan, di sana aku menemui tenda-tenda kecil teramat sederhana. Papa. Mama. Adikku. Itulah manusia pertama yang kucari. Dan, hanya sial yang kujumpai. Di sana, aku hanya menemukan adikku.
Papaku sudah tiada. Mamaku sudah tiada. Aku menggenggam tangan erat-erat. Marah. Tidak terima dengan tangan-tangan serekah yang menyebabkan banjir bandang. Siapa dia? Aku bertanya dalam hati, menggerutu.
“Nak, Vino.” Pak Sapto, kepala sekolah menyapaku dengan suara tak berenergi. Ia melangkah terhuyung mendekatiku, memelukku dengan rasa iba.
“Apa yang terjadi, Pak?” Aku bertanya lirih.
“Banjir bandang telah menenggelamkan desa kita, Nak. Semuanya karena penebangan pohon secara ilegal, sampah yang menumpuk di saluran sungai, dan hujan deras yang mengguyur desa ini. Tujuh hari tujuh malam.” Pak Sapto menjelaskan panjang lebar.
Aku diam terhenyak, tak bisa membayangkan.
“Lalu kemana ibu dan bapakku, Pak?” Aku bertanya penasaran, menunggu jawaban yang terbaik dari Pak Sapto.
Pak Sapto diam beberap saat. Aura wajahnya seperti menimbang-nimbang jawaban dan memilih bahasa yang tepat. Aku menunggu penasaran.
“Maafkan orang tua ini, Nak. Papamu ditahan di kantor polisi karena tersangka dan terbukti melakukan penebangan pohon secara ilegal. Ibumu hilang terseret banjir. Adikmu untung ditolong Arif, anak bisu kakak Vina.”
Mendengar jawaban itu badanku lemas lunglai tak berdaya. Tidak mungkin. Aku tidak percaya.
Papaku biang dari semuanya. Mamaku terseret arus. Adikku ditolong Arif. Arif itu kakak Vina.
Hanya bisikan tak bermakna itu yang dapat kulakukan. Hanya penyesalan tak berarti itu yang bisa kuperbuat.
Aku seperti di alam mimpi.
***
Seminggu kemudian aku menerima surat dari Vina.
Kak Vino, andai kau tahu kalau di dalam hatiku hanya ada kamu maka kamu tidak akan secepat ini mengambil keputusan. Kak Vino, ternyata kamu masih belum percaya kepadaku karena jika kamu benar-benar percaya tidak akan ada akhir dari sebuah cinta seperti ini.
Terima kasih ya Kak, atas cintamu, kasih sayangmu, kejujuranmu, perhatianmu, dan rindumu selama ini. Dan sekarang, terjadi sudah apa yang pernah aku hawatirkan saat kita duduk mesra menatap pucuk-pucuk tanaman padi yang menguning itu. Semuanya telah menjadi kenangan, Kak.
Bolehkan Vina melipat kenangan itu, lalu menaruh rapi-rapi di laci pikiran, kemudian esok-esok, capat atau lambat, Vina akan membukanya kembali agar Vina tidak lupa bahwa di dunia ini Vina pernah mempertaruhkan jiwa dan raga demi seorang laki-laki. Dan teruntuk laki-laki itu, dialah Vino, sebuah nama yang tidak akan pernah berhenti Vina sebutkan dalam sembah sujudku agar bahagia selalu mengiringi langkahnya.
Aku menangis sejadi-jadinya. Oh, Tuhan, sekarang, apalah arti air mata ini? Oh, Tuhan, saat ini, apalah makna tangis pilu ini?[]
Selesai. ..